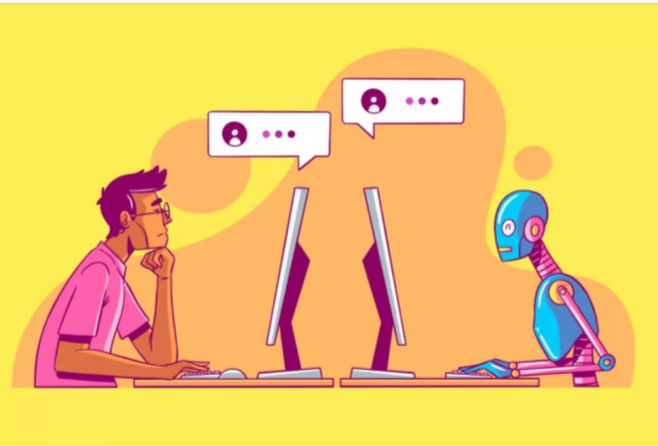Dosen Program Pendidikan Profesi Psikologi Universitas Surabaya (Ubaya), Afinnisa Rasyida, M.Psi., Psikolog., menjelaskan, CHatGPT dapat menjadi alat pendukung, namun bukan pengganti tenaga profesional kesehatan mental seperti psikolog.
“Masyarakat perlu memahami kapan bisa menggunakan ChatGPT sebagai support. Misalnya untuk membantu manajemen stres ringan, kondisi overthinking, butuh diskusi dan refleksi diri. Bukan untuk mengganti layanan profesional, khususnya pada kasus yang sudah mengganggu keberfungsian individu seperti depresi berat atau risiko bunuh diri,” jelasnya, Minggu (18/5).
Afinnisa menambahkan, maraknya fenomena ini disebabkan oleh pengguna yang ingin mendapat dukungan emosional dengan akses yang mudah, murah, dan bebas konsekuensi sosial.
Sesuai teori Help-Seeking Behavior di bidang psikologi, seseorang yang mencari bantuan sangat dipengaruhi oleh faktor personal, sosial, dan struktural.
Misalnya rasa takut mendapat stigma, keberatan dengan harga dan lokasi, serta keterbatasan tersedianya psikolog terdekat. Sehingga, ChatGPT dipilih sebagai alternatif yang paling terjangkau.
Meski demikian, Afinnisa menyebut ChatGPT memiliki risiko kesalahan dalam memahami pertanyaan atau jawaban sehingga hanya memberikan ketenangan yang bersifat sementara.
“ChatGPT tidak mampu memahami kondisi krisis kita secara mendalam. Karena analisanya bersifat umum. Juga tidak bisa memberikan penilaian (asesmen) dan intervensi yang tepat. Kita harus ingat bahwa AI tidak dapat menggantikan intervensi klinis untuk kasus berat,” tegasnya.
Wakil Direktur Pusat Konsultasi dan Layanan Psikologi Ubaya itu juga memberikan alternatif lain untuk mengekspresikan emosi dan menjaga kesehatan mental. Menurutnya, menulis jurnal dapat menjadi alternatif untuk mencatat pola emosi dan pemicu stres.
Sumber: Radar Surabaya